Oleh: Benyamin Lagowan
- Pengantar
Poin saya di sini adalah: tidak pernah dikenal sistem bayar kepala dalam budaya perang suku asli antar aliansi dan sub suku di Wamena maupun Lapago secara umum. Meski (mungkin) akhirnya budaya ini masuk pasca hadirnya pihak missi/zending dan pemerintah dengan produk firman Tuhan maupun konstitusi negara. Namun, mengapa pemerintah terlihat ikut terlibat jauh untuk membiayai pembayaran kepala yang melibatkan anggota aliansi suku tertentu, dan anggota aparat keamanan tertentu? Mestinya bilamana pelakunya aparat keamanan (TNI/POLRI), maka idealnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara bila pelakunya adalah anggota masyarakat aliansi B, C dll, maka mestinya pemerintah turut memediasi penyelesaian konflik perang suku bilamana perlu/harus. Apabila tidak, maka pemerintah tak perlu ikut campur terlibat khususnya dalam cipta kultur baru sistem bayar kepala hari ini. Pemerintah mestinya tetap menegakkan hukum pada personalia yang diduga menjadi pelaku dll dlsb. Sebab bila tidak akan hasilkan impunitas dan akan terus melangggengkan pertumpahan darah secara tak berkesudahan antar sesama masyarakat.
- Kultur Sistem Perang Suku Tradisional
Dalam 5 tahun terakhir, ada muncul sistem dan paradigma baru yang mulai terlihat terjadi di Wamena- Lapago. Paradigma dan sistem itu yakni sistem bayar kepala manusia atau transaksi jual beli kepala manusia. Awalnya sistem ini tidak dikenal dalam konsep maupun praktek kebudayaan orang Lapago. Dalam sistem perang tradisional pra Zending/Misi dan pemerintah, tidak ada konsep berperang lalu jedah kemudian terjadi rekonsiliasi/pertemuan untuk perdamaian atau urus masalah antar korban dan pelaku. Berapapun jumlah korban dari suatu perang suku, apapun motifnya, siapa salah dan benar, siapa pelaku dan siapa korban dll, tidak pernah diselesaikan melalui mediasi, melainkan bila ada aliansi yang kalah akan takluk, bermigrasi atau anak-istri diambil oleh aliansi pemenang. .
Keunikan dari sistem perang tradisional yakni justeru setiap korban (ap warek) akan dimiliki, digunakan pihak pelaku (pemenang perang/wim) bukan fisik korban tetapi berupa simbol atau perkakas tertentu dari korban sebagai sumber kekuatan dalam berperang melawan pihak korban atau musuh lainnya dikemudian hari. Menurut versi orang tua, hal itu dilakukan dengan ritual menekan roh para korban agar tidak mendatangkan kekalahan dan justeru memihak mereka mengalahkan musuh lainnya. Jadi dalam sistem perang tradisional tidak pernah sama sekali dikenal sistem mediasi, perundingan atau penyelesaian masalah melalui mekanisme apapun. Yang berlaku dulu, bila suku A vs B, lalu suku A menang, maka suku B terima kekalahan. Konsekuensinya suku B akan takluk, bermigrasi/ mengungsi ke keluarga sekitar di aliansi sekutu, aliansi kerabat sekitar dan menunggu hingga kelak mereka siap untuk melakukan pembalasan lagi.
Jadi tidak dikenal istilah korban-pelaku. Maka tidak ada juga namanya pelaku bayar kepala korban antar aliansi yang berperang. Mengapa bisa demikian? Jawabannya erat kaitannya dengan sistem falsafah hidup yang ada. Lebih utama dan umum berkaitan dengan keyakinan akan perlunya suatu korban (sacrifice) bagi kehidupan yang lebih baik. Dikarenakan paradigma bahwa semua kesialan, gagal panen, musibah, penyakit, kematian yang misterius biasanya dikaitkan kepada pihak musuh (wim silih) sehingga menuntut peperangan untuk menangkal atau keluar dari kondisi/hal tersebut.
- Sistem Perang Pasca Zending/Missi dan Pemerintah
Paradigma perang tradisional yang kuat dan sarkastik itu pun akhirnya berangsur-angsur menurun tensi, intensitas dan frekuensinya. Hal itu terkait erat dengan respon awal pihak missi dan pemerintah Belanda untuk menghentikan konflik antar suku di Wamena yang dulu sangat tinggi kasusnya. Adalah melalui program Pasifikasi semua praktek budaya yang dianggap akan mendatangkan penderitaan dalam hidup umat manusia diajak untuk dihentikan. Misalnya perang suku, Upacara Ap Waya, Pesta Wam Eweako, Ritual Potong Jari, Potong Telinga, Poligami, hingga praktek sistem Jodoh.
Penyelesaian sengketa atau konflik pun mulai menggunakan sistem dimediasi agar tidak terus mengorbankan banyak nyawa. Pihak missi dan Pemerintah menjadi fasilitator perdamaian. Akhirnya semua masalah bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi. Pada tahun 1985 ketika terjadi perang suku terakhir antar aliansi Wouma dan Welesi, oleh Bupati Jayawijaya Alber Dien dilalukan rekonsiliasi ditandai dengan menindis ubi jalar masak (hipere pusuk-pusuk) antar kedua aliansi sehingga terjadi kesepakatan damai antar dua pihak hingga saat ini.
Konsep rekonsiliasi dan perdamaian antara para pihak terjadi seiring hadirnya pihak luar (outsider) yang masuk. Dimana mereka sendiri menjadi fasilitator. Dari sini kemudian dikenal istilah rekonsiliasi (islah) antar pihak bertikai oleh orang Wamena. Demi mengurangi balas dendam dan terciptanya masalah serupa, maka disepakati akan saling bayar membayar sesuatu berupa material entah barang dan hewan ternak. Dari sinilah tercipta dan dikenal istilah dan pentingnya memahami mana pihak korban dan pelaku, sehingga kedua belah pihak dapat menerima posisi mereka setelah diuraikan pokok perkara yang menjadi pencetus awal.
Dalam situasi itu, peran ajaran agama dan edukasi sosial mengenai hukum positif pemerintah dan hukum cinta kasih yang berangkat dari Kitab Suci/Alkibat (firman Tuhan) juga turut memainkan peran besar sehingga masyarakat Wamena bisa terbiasa menerima sistem rekonsiliasi oleh pihak ketiga yang netral sebagai mekanisme baru dalam menyelesaikan suatu persoalan khususnya seperti kasus perang antar aliansi selama ini.
- Kultur Bayar Kepala Oleh Pemerintah sebagai Jalan Tol Kepunahan Etnis
Perlu digaris bawahi bahwa rekonsiliasi dalam perang yang dibahas di atas adalah yang terjadi hanya antar aliansi masyarakat intra OAP di Wamena. Tidak melibatkan Non OAP atau bahkan unsur negara. Negara memiliki semua suprastruktur dan sarana prasarana termasuk Uang yang sangat banyak jumlahnya. Kehadiran negara telah menjadi rumah besar seluruh suku-suku bangsa yang dulu hidup otonom dan terpisah-pisah tidak hanya di Wamena tetapi seluruh teritori Indonesia. Negara menjadi rumah besar bagi semua entitas aliansi, sub suku, suku – bangsa masyarakat yang berada di wilayahnya.
Lantas apakah wajar negara berperang suku lagi dengan warganya sendiri? Apakah pantas negara membunuh rakyatnya lalu membayar kepala masyarakatnya sendiri? Idealnya negara tetap menjadi tiang penopang, honai bagi rumah bersama semua entitas manusia di dalamnya. Negara mestinya menegakkan konstitusinya di atas segala-galanya. Sehingga bilamana ada terjadi konflik berbau SARA negara bertindak sebagai negosiator, mediator perdamaian dan barier pengaman yang netral dan independen. Apalagi yang terjadi antara anggota masyarakat atau rakyatnya sendiri.
Bila negara terkesan memihak salah satu korban, misalnya seperti dalam kasus konflik perang 2022 lalu antar Sub suku Nduga vs Lanny, negara mestinya tidak mengeluarkan uang untuk membayar kepala sebagai denda adat kasus pembunuhan. Harusnya negara mendukung penegakan hukum dan masyarakat yang menjadi pelaku tetap dibebankan mencari, mengumpulkan uang secara swadaya agar mereka bisa rasa bahwa mencari uang bukan perkara mudah. Dengan itu mereka bisa sadar bahwa membuat masalah lalu menyelesaikannya bukanlah perkara mudah. Dengan demikian, mereka dapat kapok dan tidak akan membuat masalah lagi di waktu-waktu mendatang. Idealnya itu.
Dalam kasus yang terbaru Wamena Berdarah Jilid 3 di Sinakma (23/02) yang menyebabkan 11 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, karena pelakunya berasal dari aparatur negara yakni Polri dan TNI, maka harusnya jalan penyelesaianya adalah tindakan tegas penegakan hukum bagi para pelaku. Mulai dari struktur komando: Kapolres, Dandim, Dansat, Kasat hingga eksekutor di lapangan dicopot lalu diberhentikan dari institusi dan dihukum pidana penjara. Ini idealnya sehingga ada efek jera agar dikemudian hari tidak terjadi lagi oleh anggota lainnya.
Bila ini terkait erat dengan misi atau agenda politik ideologi pembersihan etnis (Etnic Cleasing), maka idealnya para korban tidak menerima apapun dari pelaku sehingga mengikuti kultur budaya perang tradisional masa lalu orang Wamena di atas. Sebab dengan menerima bayar kepala maka, kepala orang Papua dikemudian hari bisa dipatok atau dianggarkan khusus seperti sayembara. Oknum2 pemerintah, penguasa dan kelompok oligarki kapanpun bisa melakukan transaksi jual beli kepala manusia di pasar gelap untuk menargetkan kepala lawan-lawan politik, musuh dalam selimut, musuh lama dll dsb. Bahkan adalah ironis bila terdapat alokasi APBD untuk bayar kepala manusia. Syukur-syukur bila tidak muncul pikiran dan wacana dibentuknya badan penyelesaian perang suku (konflik) di bawah dinas sosial yang memiliki seksi bayar kepala.
- Kesimpulan
Bila kultur baru ini tidak segera dihilangkan dan dihindari, maka ke depan saling baku bunuh secara terang-terangan antar aliansi, sub suku dan suku (horizontal) dan antar masyarakat dengan aparat keamanan (vertikal) akan terjadi di depan mata secara meluas karena alasan dasarnya pemerintah secara tidak langsung telah sahkan atau legalkan. Akan ada anggapan pemerintah akan tanggung dengan bayar kepala atau, masyarakat siap sumbang-sumbang untuk bayar kepala. Dengan demikian yang berlaku: a) sistem hukum rimba, yang kuat dan kaya yang menang ,b) hukum positif tidak berlaku untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat, c) Tujuan sekolah dan pendidikan percuma, d) Agama dan firmannya soal cinta kasih menjadi sia-sia, e) dll dsb. Akhir daripada ini, secara kuantitas dan kualitas populasi OAP akan menuju depopulasi. Sistem ini akan sangat berbahaya bagi kelompok pro kemerdekaan Papua, karena dengan ini nyawa dan keselamatan mereka akan sangat terancam. Dengan ini, maka apa yang diungkapkan oleh budayawan Baliem Agus Alua berikut akan menjadi kenyataan. “Tidak semua manusia berpikir hari ini saya makan apa, tetapi ada manusia yang setiap harinya berfikir hari ini saya akan makan siapa?” [Alua: 2003].
- Pertanyaan-Pertanyaan
Apa jadinya jika terjadi kasus pembunuhan oleh warga non OAP kepada OAP dan mereka siap bersedia bayar kepala? Apa jadinya bila anggota tertentu ingin membunuh si B dengan tebusan uang kepala sekian M? Apa jadinya bila semua kepala pentolan aktivis Papua diincar oleh negara dengan taruhan harga milyaran rupiah per kepala? Bila semua kasus-kasus pembunuhan dapat diselesaikan dengan sistem bayar kepala, maka di mana posisi dan kedudukan Hak Asasi Manusia? Bila demikian juga, maka apa gunanya keberadaan institusi kepolisian dan TNI Polri dll sebagai penegak hukum? Konsekuensi dari sistem bayar kepala, ini maka tidak akan pernah ada istilah kategori pelanggaran HAM lagi di masa depan? Lalu terakhir apakah kita harus memaknai ini adalah bentuk lain dari implementasi hukuman mati menurut konstitusi negara dan panggilan/kehendak Tuhan Allah bagi setiap umat manusia? Sebaiknya segera hentikan sistem bayar kepala yang berbahaya bagi kehidupan rakyat Papua yang makin minoritas ini.*
Jayapura, Rabu 1 Maret 2023
Penulis adalah Kordinator Forum Pemuda Anti Perang Suku dan Pro Perdamaian Wamena














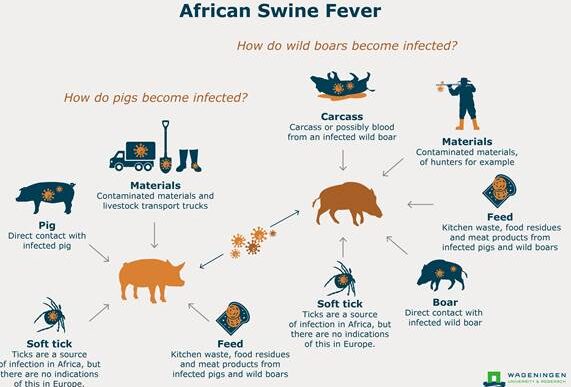





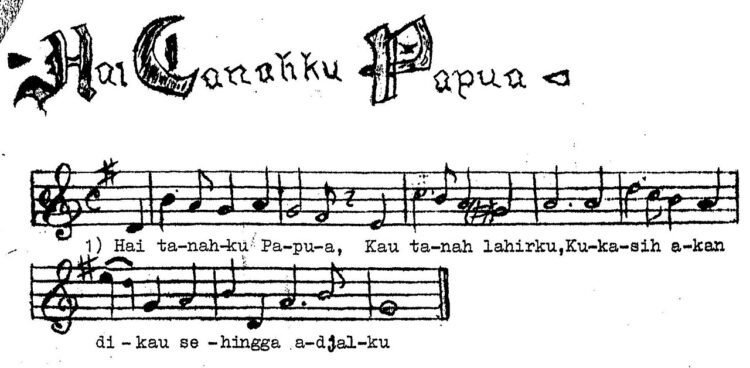
+ There are no comments
Add yours